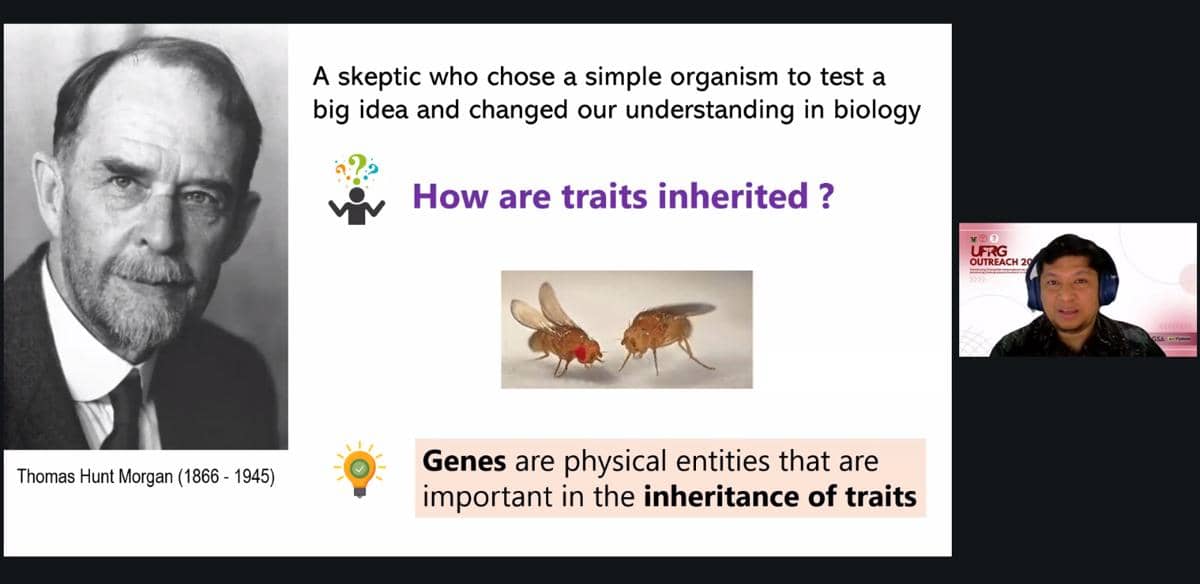Pilkada Langsung vs DPRD: Legitimasi Rakyat atau Efisiensi Anggaran?

Makassar, IDN Times - Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah terus menjadi sorotan publik. Setelah 20 tahun Pilkada digelar secara langsung oleh rakyat, kini muncul wacana untuk mengembalikannya ke DPRD.
Perubahan ini memunculkan berbagai pertimbangan terkait legitimasi, efektivitas, dan biaya politik. Pilkada langsung dikenal memberikan legitimasi kuat karena kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, dengan akuntabilitas vertikal dari eksekutif ke rakyat.
Prof. Risma Niswaty, pakar kebijakan publik Universitas Negeri Makassar, menegaskan bahwa Pilkada langsung memberikan legitimasi karena dipilih oleh rakyat langsung. Namun, sistem ini juga punya sisi lain yang tumpul karena biaya politik sangat besar.
"Pilkada seperti ini, di satu sisi, tentu saja jika Pilkada langsung tetap diterapkan, dari sudut pandang direct mandate rakyat, mereka yang memilih langsung di situ. Dari sisi legitimasi, calon tentu lebih kuat karena dipilih langsung oleh rakyat," kata Prof. Risma saat Diskusi Publik Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada di Kopitiam Hertasning Makassar, Selasa (10/2/2026).
1. Pilkada langsung punya legitimasi kuat tapi biaya politik tinggi

Risma menjelaskan masyarakat sudah terbiasa dengan pola transaksional pada Pilkada langsung yang telah digelar sejak 20 tahun terakhir. Perubahan sistem akan berpotensi menimbulkan risiko legitimasi dan instabilitas.
Dia menyampaikan bahwa masyarakat dan para calon pada awalnya masih sangat naif karena sistem Pilkada baru diterapkan. Aturannya masih sedikit, prosesnya trial and error, dan praktik transaksional memang sudah ada, tetapi tidak sebesar seperti sekarang.
"Karena di awal Pilkada langsung itu terjadi paling yang menggunakan jalur transaksional itu adalah teman-teman dari partai politik yang menjadi calon," katanya.
Dia juga menyampaikan bahwa masyarakat pada awalnya mungkin tidak sepenuhnya terkontaminasi jalur transaksional itu. Namun, setelah 20 tahun, penyelenggara Pilkada, menurutnya, turut memengaruhi masyarakat sehingga terjadi perubahan perilaku yang merugikan.
"Sekarang bertambah dengan penyelenggara Pemilu itu menjadi jahat juga. Jahat dan nakal, mau kita pakai istilah lagunya siapa itu? Nakal boleh, jahat jangan. Nah ini ternyata penyelenggara juga jadi jahat," katanya.
2. Residu dan konflik sosial sebagai efek pilkada langsung

Risma menjelaskan bahwa biaya politik pilkada sangat besar, belum termasuk anggaran negara maupun dana yang dikeluarkan calon sendiri. Biaya politik ini, menurutnya, seperti investasi yang harus kembali sehingga ada tekanan untuk mengembalikan modal melalui hasil politik yang diperoleh.
"Ini menjadi efek domino ketika biaya pilkada itu besar, maharnya besar, kemudian kampanyenya, lalu mereka juga di hari-H dengan serangan fajarnya, menyiapkan dana untuk saksi. Luar biasa, harus balik modal," kata Risma.
Dia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran pilkada juga tidak boleh langsung dianggap sebagai hal positif, karena sistem ini pasti menimbulkan efek tertentu. Menurutnya, selama 20 tahun pelaksanaan pilkada langsung, banyak residu yang dihasilkan dari proses tersebut.
Beberapa contoh residu sosial adalah konflik horizontal. Belum lagi hilangnya gotong royong, dan perubahan karakter masyarakat akibat praktik transaksional.
"Gotong royong mati loh ketika ada pilkada. Kita pernah menemukan ya, saya mungkin misalnya sangat akrab dengan Mas Firdaus, kami seperti kakak-adik tapi ketika pilkada dan pilihan kami berbeda, saya bisa nggak bertegur sapa seumur hidup sama dia. Saya kehilangan silaturahmi saya nih," kata Risma.
3. Pilkada di DPRD lebih hemat anggaran tapi risiko kepala daerah jadi boneka partai
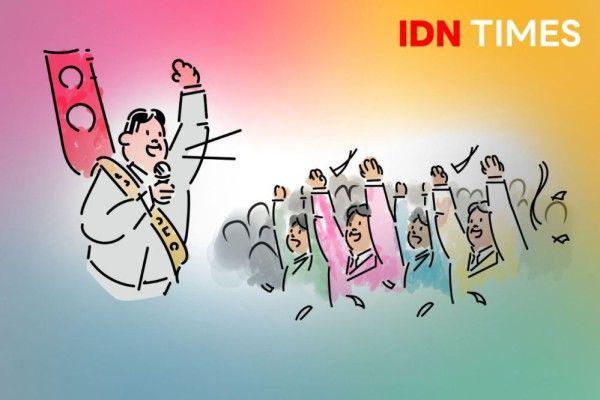
Sementara itu, pilkada melalui DPRD dipandang lebih efisien secara anggaran. Prof. Firdaus Muhammad, pakar komunikasi politik Universitas Islam Alauddin Makassar, menuturkan bahwa jika pilkada digelar di DPRD, maka anggaran bisa lebih hemat.
"Masing-masing ada plus minusnya, tetapi jauh lebih buruk kalau kembali lagi ke DPRD. Cuma apa untungnya? Anggaran efisiensi itu bisa digunakan untuk yang lain," katanya.
Dia mengingatkan bahwa tegaknya kedaulatan, wibawa, dan kelancaran sistem sebuah negara sangat bergantung pada situasi politik. Dia juga menuturkan bahwa koalisi antara DPRD dan kepala daerah bisa putus di tengah jalan, sehingga program pemerintah berisiko terhambat.
"Yang sejatinya adalah di sini ada harus ada kemitraan institusi mewakili aspirasi masyarakat. Nah kalau pemilihannya di DPRD maka sudah pasti yang pengendali utama adalah partai politik," kata Firdaus.
Dia menjelaskan bahwa pengaturan kursi DPRD dan pemilihan anggota sangat bergantung pada partai politik. Dalam DPRD, kekuatan partai lebih besar sehingga kepala daerah yang terpilih menjadi kurang dianggap dan cenderung menjadi boneka, meskipun sistemnya mirip Orde Baru.
"Jadi bisa saja apa yang dipresentasikan janji-janji politiknya tidak akan ditunaikan karena kontrol dari DPRD. Celakanya adalah kalau DPRD itu berebut pengaruh terhadap kepala daerah, makin tidak ada wibawanya kepala daerah kalau pemilihan di DPRD," kata Firdaus.
4. Risiko kemunduran demokrasi jika pilkada di DPRD

Dari perspektif sosial, Sosiolog Hasruddin Nur menekankan bahwa Pilkada yang kembali ke DPRD berpotensi menyebabkan kemunduran demokrasi. Dia menjelaskan bahwa jika Pilkada dipilih oleh DPRD, maka publik otomatis tidak akan dilibatkan dalam berbagai tahapan proses politik.
"Semuanya bermuara di DPRD. Proses komunikasi politik semuanya ada di DPRD, sudah tidak ada lagi keterlibatan masyarakat secara umum. Inilah yang sebetulnya bisa dikatakan bahwa masyarakat bisa menyebut itu kemunduran daripada sebuah demokrasi," katanya.
Dia menuturkan bahwa banyak masyarakat akan merasa dirugikan karena hak mereka untuk memilih kepala daerah direnggut. Menurutnya, masyarakat selama ini sudah sangat dirugikan dengan dirampasanya lahan mereka untuk dijadikan aset tambang.
Dia menjelaskan bahwa memilih kepala daerah merupakan hak politik masyarakat sehingga mereka ingin menentukan sendiri siapa yang menjadi pimpinan daerah. Jika Pilkada kembali ke DPRD, maka belum ada jaminan bahwa aspirasi masyarakat akan terwakili oleh anggota legislatif.
"Ada tidak jaminan bahwa tidak akan ada transaksi jual beli politik yang dilakukan oleh para legislatif dengan para calon? Itu belum ada jaminannya sampai hari ini. Bahkan mungkin saja nominal jumlahnya jauh lebih tinggi daripada transaksi Pilkada langsung," katanya.