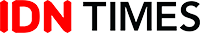Pengamat: Pilpres yang Sehat Itu Menang Berkuasa, Kalah Jadi Oposisi
 ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengkritik hasil pemilu presiden 2019 yang justru malah menghasilkan demokrasi yang tak sehat. Sebab, dua kandidat Presiden yang saling berseteru selama satu tahun terakhir, ujung-ujungnya malah berkoalisi.
Ketika ditawari kursi Menteri, Ketua Umum Partai Gerindra dan capres 2019,Prabowo Subianto malah menerimanya. Tidak tanggung-tanggung kursi yang diberikan adalah Menteri Pertahanan.
Syamsuddin justru bingung untuk apa Joko "Jokowi" Widodo mengajak Prabowo bergabung masuk ke dalam koalisi partai pendukungnya.
"Makanya, ada kompetisi di pemilu presiden. Yang keluar sebagai pemenang berkuasa, sedangkan yang kalah ya legowo menjadi opisisi. Itu seharusnya demokrasi kita yang sehat, bukan kemudian semuanya diajak masuk (jadi koalisi)," kata Syamsuddin dalam dialog dengan tema "Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II" di kafe di area Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (22/10).
Ia mengatakan apabila semua lawan saat kontestasi pemilu dibawa masuk, maka model negara kekeluargaan yang dicita-citakan oleh Soepomo pada tahun 1945 bisa terealisasi. Hal itu bisa mengancam demokrasi di Indonesia.
Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh publik agar demokrasi di pascareformasi tak dibawa mundur ke era Orde Baru?
1. Seharusnya politik yang berlaku di Indonesia adalah politik sportif
Syamsuddin sejak awal mengaku terkejut dan menyayangkan mengapa Jokowi justru mengajak Prabowo bergabung ke dalam koalisi partai pendukungnya. Ia pun juga tak habis pikir setelah selama setahun terakhir mencaci maki mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Prabowo justru bersedia masuk kabinet saat ditawari kursi Menteri.
"Mestinya Pak Jokowi gak usah lah mengajak Partai Gerindra ke dalam kabinet dan sebaliknya sebaliknya, Pak Prabowo dan teman-teman menolak lah ajakan itu. Ini kan akibat pemahaman yang dangkal, politik akhirnya seolah-olah terkesan demikian," kata dia.
Seharusnya, publik menolak konsep politik dangkal semacam itu. Sebaliknya, politik yang menjunjung tinggi adalah yang menghargai posisi masing-masing, baik itu sebagai koalisi atau oposisi.
"Jadi, itu yang dinamakan politik yang menjunjung tinggi sportivitas, di mana yang kalah mengakui yang menang dan yang menang merangkul yang kalah. Tetapi, bukan maksudnya merangkul masuk ke dalam pemerintahan ya," tutur dia lagi.
Ia pun mempertanyakan apabila ujung-ujungnya Jokowi dan Prabowo berada di satu posisi, untuk apa pada April lalu digelar pemilu. Apalagi pemilu legislatif dan presiden harus dibayar dengan biaya mahal dan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.
"Ini kan sama saja kalau di kompetisi sepak bola, semua dapat piala," katanya.
Editor’s picks
Baca Juga: Jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Bakal Kelola Anggaran Besar
2. Di Indonesia, parpol tak ingin dilabeli sebagai oposisi karena tak bisa mengganti kekuasaan
Lalu, mengapa di Indonesia tak ada satu pun partai politik yang ingin berada di barisan oposisi? Menurut Syamsuddin penyebabnya ada dua. Pertama, ketika berada di kelompok oposisi, tidak ada insentif politik untuk mengganti pemerintahan. Sebab, dalam sistem pemerintahan yang menganut presidensil jabatan presiden sudah ditentukan lima tahun lamanya. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer yang kapan pun yang memimpin bisa berganti.
"Kedua, di dalam sistem politik di Indonesia, tidak ada budaya oposisi. Sehingga semua partai politik tidak mau disebut sebagai oposisi, mulai dari PDIP sampai Demokrat maunya disebut sebagai penyeimbang," kata dia menjawab pertanyaan IDN Times pada hari ini.
Penyebutan sebagai oposisi itu, kata Syamsuddin, merupakan kultur liberal.
"Konteksnya jadi negatif. Nah, mereka tidak mau itu," ujar Syamsuddin.
3. Presiden Jokowi seharusnya menyusun kabinet di jilid II berdasarkan kebutuhan dan tantangan
Syamsuddin juga mengingatkan Jokowi agar membentuk kabinet dengan mengutamakan tantangan dan kebutuhan. Bukan malah mengedepankan sikap kompromi dan mengakomodir kepentingan berbagai pihak.
Apa saja tantangan ke depan yang dihadapi oleh Indonesia?
"Pertama, ancaman terhadap toleransi, kebhinnekaan dan persekusi berbasis sektarian. Sayangnya, poin itu tidak muncul di pidato Presiden kita. Ancaman serius lainnya yakni korupsi yang betul-betul merajalela. Kemudian, ada pula ancaman terhadap demokrasi yang semakin diambil alih oleh oligarki baik yang menguasai politik di Senayan dan yang mencengkeram sumber daya alam," tutur dia.
Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam upaya menegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI tersebut seharusnya memilih Menteri berdasarkan rekam jejak dan tokoh yang bersih.
"Hal itu berarti bebas dari korupsi, pelanggaran HAM dan tindakan persekusi, intoleransi serta diskriminasi," katanya.
Baca Juga: Pidato Lengkap Jokowi Usai Dilantik Jadi Presiden RI 2019-2024